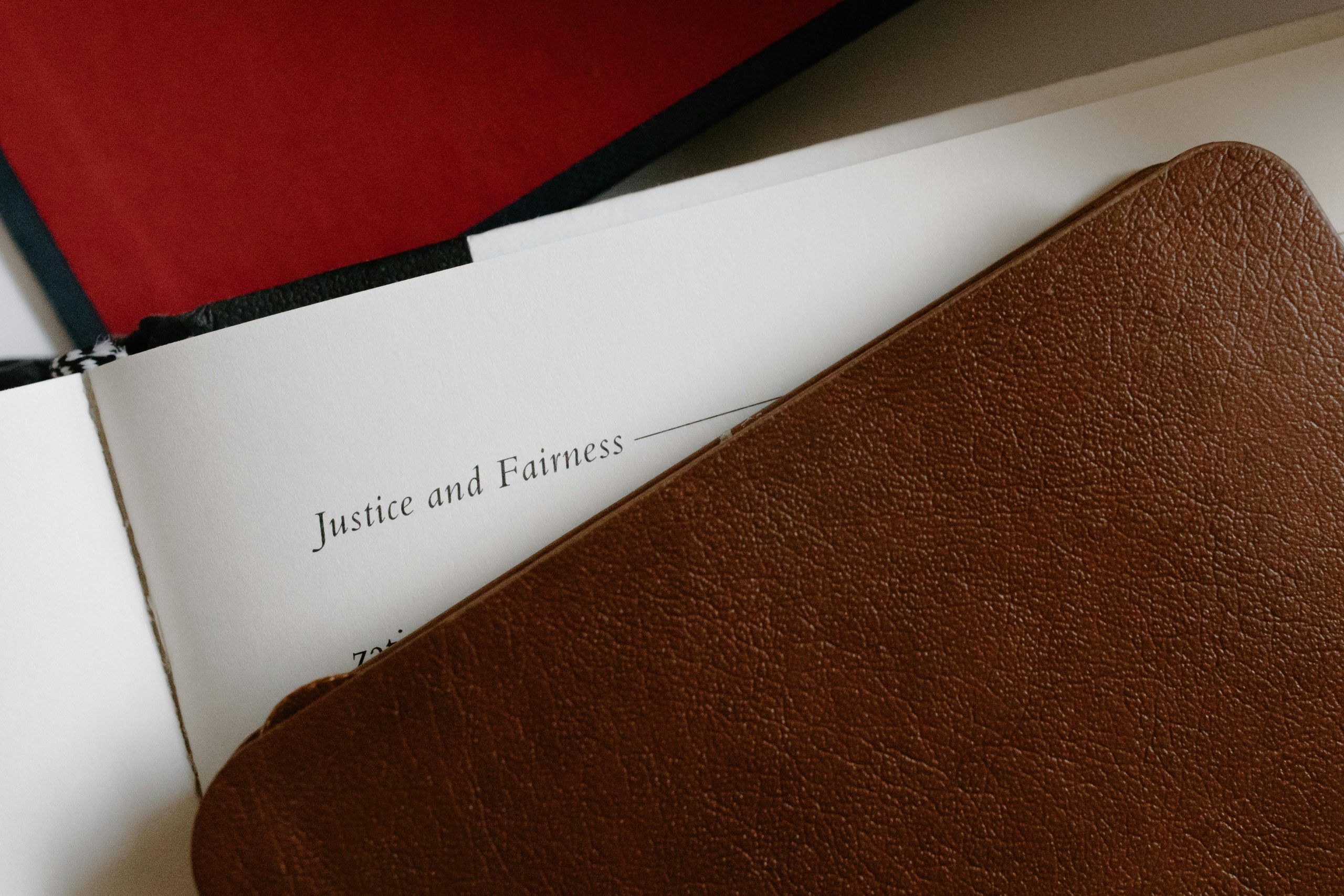Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa negara hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam konsep ini, seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan hukum berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang.
Seiring perkembangan teori dan praktik ketatanegaraan, bentuk negara hukum berkembang ke dalam berbagai varian yang dikenal dan dipelajari secara akademik, yakni Rechtsstaat, Rule of Law, Welfare State, dan Negara Hukum Pancasila.
Konsep Rechtsstaat berasal dari pemikiran hukum Eropa Kontinental, khususnya Jerman dan Belanda. Friedrich Julius Stahl menjadi tokoh utama dalam merumuskan bentuk negara hukum ini. Ia menekankan bahwa negara hukum harus didasarkan pada empat unsur, yaitu perlindungan hak asasi manusia, legalitas dalam setiap tindakan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan adanya peradilan yang independen. Dalam model ini, supremasi hukum bersifat formalistik dan mengutamakan aturan hukum tertulis sebagai batas kekuasaan negara. Pendekatan ini banyak diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum civil law.
Sementara itu, Rule of Law merupakan konsep negara hukum yang berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon. A.V. Dicey mengemukakan bahwa Rule of Law mengandung tiga prinsip utama, yakni supremasi hukum atas segala bentuk kekuasaan, persamaan semua orang di hadapan hukum, dan jaminan perlindungan hak-hak dasar melalui pengadilan yang bebas dari intervensi. Tidak seperti Rechtsstaat, pendekatan Rule of Law tidak selalu bergantung pada hukum tertulis, tetapi lebih menekankan pada keadilan substantif yang hidup dalam praktik pengadilan dan nilai-nilai moral masyarakat.
Seiring berkembangnya tuntutan terhadap keadilan sosial, muncul bentuk negara hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, yakni Welfare State atau negara hukum kesejahteraan. Negara hukum ini tidak cukup hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara harus hadir dalam pemenuhan hak-hak sosial ekonomi warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam bentuk ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Negara hukum kesejahteraan telah menjadi model di banyak negara yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan negara.
Indonesia menganut bentuk negara hukum yang khas, yakni Negara Hukum Pancasila. Indonesia tidak sekadar mengikuti satu model tertentu, melainkan menyinergikan unsur-unsur terbaik dari Rechtsstaat, Rule of Law, dan Welfare State dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Negara hukum Pancasila menempatkan hukum dalam konteks yang berkeadaban, bermoral, dan sesuai dengan budaya bangsa. Dalam model ini, supremasi hukum tetap dijaga, namun selalu dikaitkan dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk negara hukum memiliki akar yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menata kekuasaan berdasarkan hukum dan melindungi hak warga negara. Indonesia melalui Negara Hukum Pancasila telah membangun model yang bersifat integral: mengedepankan hukum yang adil, responsif terhada kesejahteraan, dan selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa. Bentuk ini mencerminkan cita-cita luhur untuk menjadikan hukum sebagai sarana mencapai keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab.

Intern at Ambarsan & Partners Law Firm